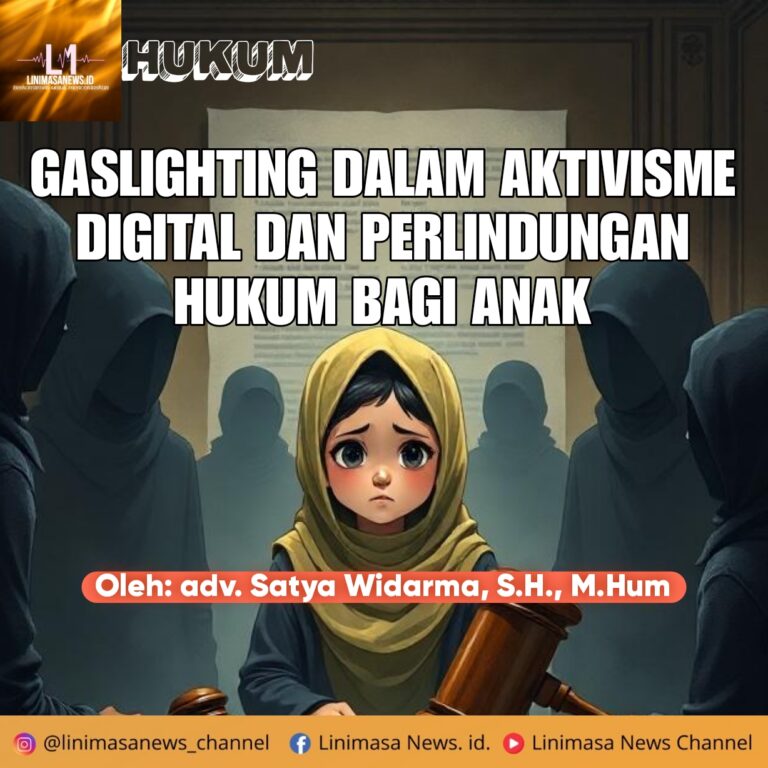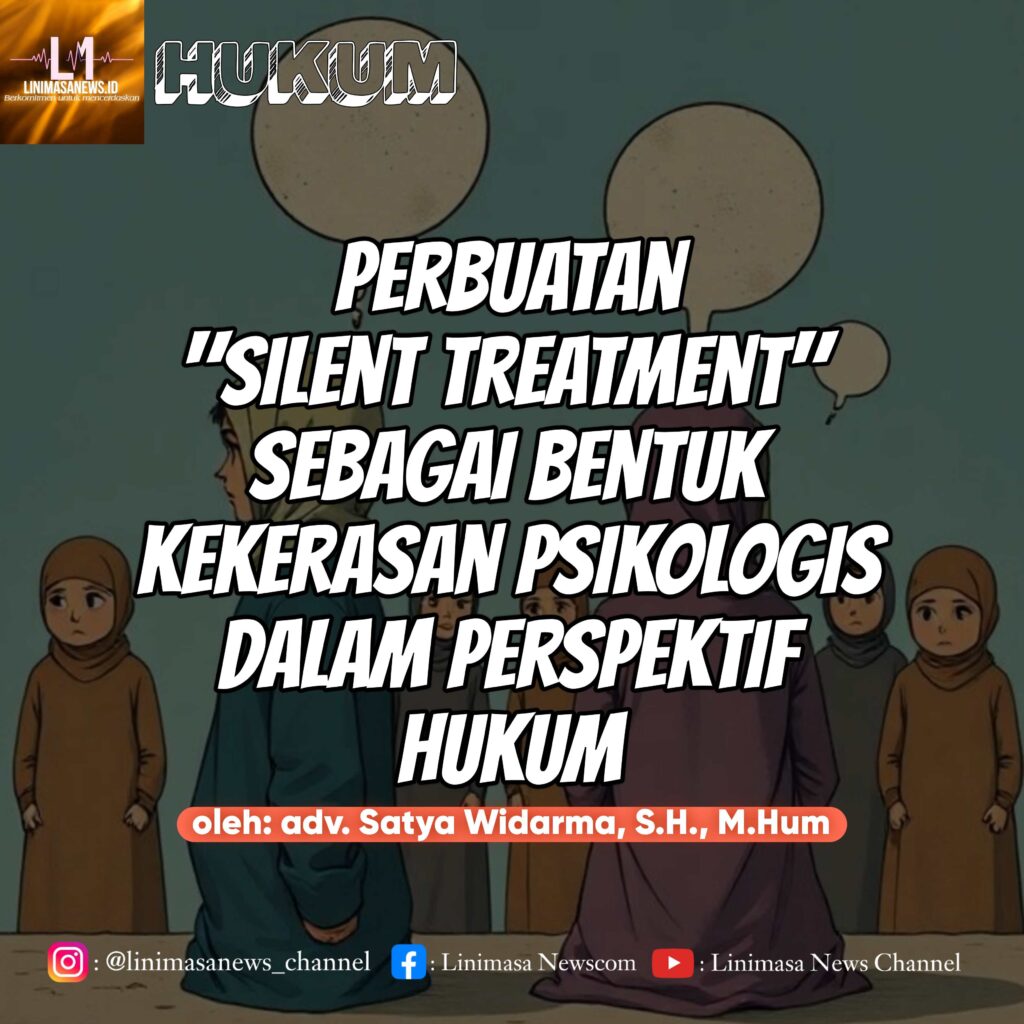
Oleh: adv. Satya Widarma, S.H., M.Hum.
Linimasanews.id—Kekerasan memiliki unsur perbuatan yang bernuansa memaksa, menyebabkan cedera, menyebabkan kerusakan dan selain berwujud fisik, juga dapat secara psikis. Dalam konteks hubungan interpersonal, baik dalam ruang lingkup rumah tangga, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan sosial, kekerasan psikologis sering kali dipandang remeh, bahkan cenderung diabaikan karena sifatnya yang tidak tampak secara kasat mata.
“Silent treatment” adalah salah satu dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan kepada korbannya secara psikis. Bentuk tindakannya seperti bersikap abai, sengaja tidak berkomunikasi dengan seseorang, dalam rangka manipulasi, menghukum, atau mengontrol emosi korban. “Silent treatment” adalah pokok bahasan utama yang dalam artikel ini dikaji menurut hukum Indonesia.
“Silent treatment refers to a range of behaviors such as removal of eye contact, not talking and listening, which are purported to avoid verbal communication or/and ignore the other person” (“Silent treatment mengacu pada serangkaian perilaku seperti menghindari kontak mata, tidak berbicara maupun mendengarkan, yang bertujuan untuk menghentikan komunikasi verbal dan/atau mengabaikan orang lain) (Williams, 1997).
“Silent treatment” merupakan perbuatan berupa pengabaian secara sengaja dengan tujuan atau motif agar menimbulkan perasaan terisolasi, menimbulkan perasaan tidak dihargai, atau menyebabkan rasa tidak berdaya pada korbannya. Perbuatannya bisa berupa menghindari kontak mata, tidak mau mendengarkan atau berpura-pura tidak mendengarkan korban. Perbuatan ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, seperti stres, rasa cemas, depresi, dan bahkan trauma emosional. Dalam konteks hukum, kekerasan psikologis diakui sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk diperlakukan dengan hormat dan tanpa kekerasan.
Istilah “silent treatment” pertama kali digunakan oleh para pelaut untuk merujuk pada hukuman sosial terhadap orang-orang di laut (Ferguson, 1944). Secara serupa, “Meidung” dipraktikkan oleh komunitas Amish untuk mengucilkan seseorang secara sosial yang telah melanggar aturan agama atau budaya (Gruter, 1986), di mana anggota komunitas, bahkan teman dekat dan keluarga, dilarang berbicara atau berinteraksi dengan pelanggar tersebut. Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan “silent treatment” adalah “cold shoulder”, “freezing out”, “sent to coventry” dan dalam bahasa slang Australia “treating with ignore”. (Wilkes, 1990).
Di Indonesia, kekerasan psikologis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang menyebutkan bahwa kekerasan psikologis termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. “Silent treatment” menurut peraturan ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikologis jika dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga dan menimbulkan cedera atau derita secara psikis pada korban.
2. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan penganiayaan yang mencakup penganiayaan fisik dan juga psikis. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut “silent treatment“, menurut peraturan ini, “silent treatment” dapat dianggap sebagai perbuatan menganiaya jika terbukti perbuatan itu menimbulkan derita secara psikis pada korban.
3. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Menurut ketentuan ini, “silent treatment” dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang merendahkan martabat jika dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti atau mengendalikan korban secara psikis.
Pelaku “silent treatment” tentu tidak lepas dari dampak hukum, yang apabila terbukti melakukan kekerasan psikologis, dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam ruang lingkup rumah tangga, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ancaman pidananya maksimal 3 tahun penjara atau denda. Selain itu, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi.
Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh korban silent treatment adalah seperti:
1. Membuat laporan kepolisian atau lembaga layanan korban kekerasan;
2. Mengajukan permohonan perlindungan korban ke pengadilan melalui Surat Perintah Perlindungan (SPP) berdasarkan undang-undang (Vide: Pasal 27 sampai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);
3. Mencari bantuan kepada profesional, seperti psikolog maupun advokat/pengacara untuk memulihkan kondisi mental, emosional dan memahami situasi hukum yang dialami.
Pada beberapa temuan penelitian, “silent treatment” tidak selalu digunakan untuk menguasai suatu hubungan. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, “silent treatment” justru dipakai ketika seseorang berada dalam posisi yang lebih lemah dalam hubungan (having lower power in the relationship), sebagai cara untuk mengekspresikan penolakan tanpa membuat pihak lain marah (show disagreement without making the target angry) dan berisiko kehilangan hubungan serta manfaat atau imbalan sosial yang diperoleh darinya (contingent rewards).
“Silent treatment” adalah bentuk kekerasan psikologis yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korbannya. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga.
Penting bagi masyarakat untuk menyadari tentang salah satu kekerasan psikologis ini, yaitu “silent treatment”, karena merupakan perbuatan yang berbahaya dan berimplikasi secara hukum. Karenanya, korban pada khususnya, harus diberdayakan agar keselamatan dan keamanannya dapat terjamin dan keadilan dapat terwujud melalui mekanisme hukum yang tersedia dan masyarakat pada umumnya lebih waspada dan peduli dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan psikologis.