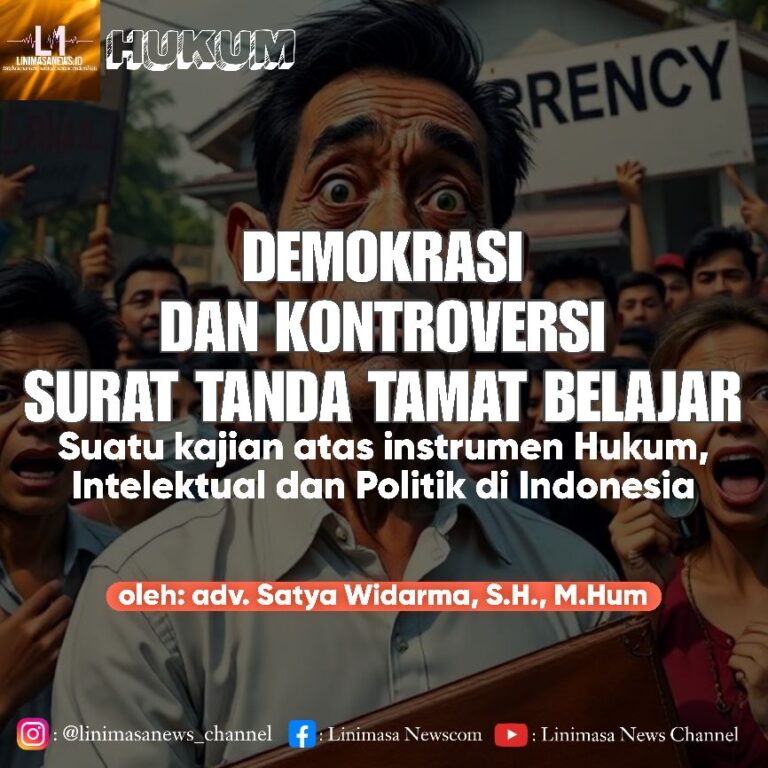Oleh: Satya Widarma, S.H., M.Hum
Linimasanews.id—Pada tahun 2020, video TikTok seorang remaja berusia 17 tahun tentang kebrutalan aparat penegak hukum di Amerika Serikat viral dengan 50 juta tayangan dalam sehari. Konten tersebut tidak hanya memicu gelombang diskusi, tetapi juga menjadi penggerak demonstrasi hak sipil terbesar dalam sejarah negara itu. Fenomena serupa terjadi di Indonesia, di mana aktivisme digital generasi muda seperti kampanye lingkungan, atau anti-korupsi kian mengemuka. Sayangnya, upaya – upaya ini sering kali dihadapkan pada praktik gaslighting, yaitu manipulasi psikologis yang meragukan validitas suara dan kontribusi anak muda. Melalui perspektif hukum Indonesia, fenomena ini perlu dikaji dengan menimbang prinsip perlindungan anak, kebebasan berekspresi, dan keadilan sosial.
Aktivisme digital telah menjadi instrumen transformatif bagi generasi muda untuk mengubah wacana publik, memberi suara kepada kelompok terpinggirkan, dan menggerakkan solidaritas global. Disebut dalam literatur, “..moreover, research on youth activism has often centred on use of digital media, including the use of mobile phones for communicating and documenting action, use of the Internet for gathering and disseminating information, or the use of social media to connect to other activists as well as to outside audiences (Vide: Jenkins, 2016). Indeed, youth activists tend to be early adopters of novel digital media strategies with the aim of speaking to a youth audience (Vide : Kligler-Vilenchik and Literat, 2024). (Selain itu, penelitian mengenai aktivisme pemuda sering kali berfokus pada penggunaan media digital, termasuk penggunaan ponsel untuk berkomunikasi dan mendokumentasikan aksi, penggunaan Internet untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi, atau penggunaan media sosial untuk terhubung dengan aktivis lain serta audiens luar (Vide : Jenkins, 2016). Memang, aktivis pemuda cenderung menjadi pengadopsi awal strategi media digital yang inovatif dengan tujuan menjangkau audiens muda (Kligler-Vilenchik dan Literat, 2024).
Namun sayangnya, ekspresi ini kerap dipandang sebelah mata oleh generasi sebelumnya yang terbiasa dengan bentuk aktivisme konvensional, seperti demonstrasi jalanan atau lobi langsung ke pemangku kebijakan. Komentar semacam, “Ini hanya tren” atau “Kamu belum paham kompleksitas isu” atau “anak kemarin sore”, mungkin terkesan sepele, tetapi secara psikologis berpotensi merusak kepercayaan diri anak muda. Dalam konteks hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang dilarang Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Pasal 15 Undang-undang ini secara tegas menjamin hak anak untuk dilindungi dari keterlibatan dan penyalahgunaan yang keliru, termasuk bentuk pelecehan yang merendahkan upaya partisipasi mereka di dunia maya.
Konstitusi Indonesia telah mengakui aktivisme digital sebagai perwujudan hak asasi. Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sementara Pasal 28C ayat (2) mengakui hak setiap orang untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif. Dengan demikian, upaya meremehkan partisipasi digital anak muda tidak hanya bertentangan dengan semangat konstitusi, tetapi juga mengabaikan realitas era modern: platform digital telah mengubah cara masyarakat terlibat dalam isu sosial. Gerakan seperti #MeToo (gerakan sosial yang bertujuan untuk mengangkat kesadaran dan memperjuangkan hak-hak korban pelecehan dan kekerasan seksual) dan Black Lives Matter (gerakan sosial dan politik global yang bertujuan untuk melawan rasisme, diskriminasi, dan ketidaksetaraan rasial yang dialami oleh orang kulit hitam), membuktikan bahwa mobilisasi online mampu berintegrasi dengan aksi fisik untuk menciptakan dampak nyata. Di Indonesia, kampanye lingkungan yang diinisiasi aktivis remaja di Kalimantan melalui Instagram—meski dihujat dengan komentar “Kamu masih kecil, tidak paham urusan orang dewasa”, berhasil menyadarkan publik tentang dampak deforestasi terhadap masa depan generasi muda.
Praktik gaslighting terhadap aktivisme digital juga melanggar asas hukum fundamental. Pertama, asas kepentingan terbaik anak (best interest of the child) menuntut negara dan orang tua untuk memastikan partisipasi anak dalam proses demokrasi. Kedua, asas non-diskriminasi melarang perlakuan tidak adil terhadap anak muda, terutama dari kelompok marginal seperti penyandang disabilitas. Misalnya, diskriminasi terhadap Alya Putri, seorang mahasiswi penyandang disabilitas fisik asal Jakarta yang menggunakan kursi roda, yang kontennya fokus pada isu aksesibilitas transportasi umum dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Dalam videonya, ia merekam perjalanannya menggunakan Transjakarta, MRT, dan stasiun kereta sambil mengkritik minimnya fasilitas ramah disabilitas, seperti lift rusak atau jalur khusus yang terhalang. Kontennya kerap viral, dengan rata-rata 100.000 penonton per video.
Namun, upayanya ini tidak lepas dari tantangan. Pada Maret 2023, video Alya tentang ketiadaan akses kursi roda di halte Transjakarta Bundaran HI memicu respons negatif secara masif. Sejumlah akun anonim mengirim komentar seperti, “Ngapain ribut-ribut? Mending di rumah aja daripada merepotkan orang lain,” “Cuma cari perhatian! Orang cacat kok sok jadi aktivis,” hingga tuduhan bahwa kontennya hanya mencari donasi dari luar negeri. Tidak hanya komentar merendahkan, Alya juga mengalami perundungan (cyberbullying) melalui pesan pribadi, termasuk ancaman doxing (penyebaran data pribadi). Parahnya, beberapa pengikut melaporkan kontennya sebagai spam ke TikTok, sehingga jangkauan videonya berkurang drastis.
Dampak psikologis yang dialami Alya cukup serius. Ia mengaku sempat mengalami kecemasan dan enggan membuat konten selama sebulan. “Saya hanya ingin transportasi umum bisa diakses semua orang. Tapi yang saya dapat malah dikata-katai seolah saya tidak punya hak bersuara,” ujarnya dalam wawancara dengan media. Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan moral, tetapi juga terdapat pelanggaran hukum. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat (Pasal 5) dan perlindungan dari diskriminasi (Pasal 11). Komentar bernada merendahkan dan ancaman doxing terhadap Alya jelas bertentangan dengan hal ini. Selain itu, Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) melarang perbuatan yang bersifat penghinaan, sementara Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 ayat (3) melindungi setiap orang dari perlakuan diskriminatif. Kisahnya menjadi pengingat bahwa ruang digital harus menjadi ruang aman bagi semua suara, termasuk mereka yang memperjuangkan hak-hak marginal. Ketiga, asas keadilan prosedural menegaskan bahwa suara anak muda berhak didengar tanpa prasangka, termasuk dalam ruang digital.
Bahwa untuk melindungi generasi muda dari gaslighting, diperlukan sinergi antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Orang tua didorong untuk mendengarkan aspirasi anak tanpa menghakimi, labelling, memvalidasi upaya mereka, serta menghindari bahasa yang bernuansa merendahkan. Negara juga harus hadir dengan mengoptimalkan penegakan Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3), yang melarang konten penghinaan di media sosial. Komentar seperti “Ini cuma tren” dapat dilaporkan sebagai bentuk pelecehan psikis. Selain itu, Kementerian Pendidikan perlu mengintegrasikan literasi media dan hak berekspresi ke dalam kurikulum pendidikan, merujuk Permendikbud No. 22 Tahun 2020.
Bagi kelompok marginal, perlindungan hukum harus diperkuat melalui implementasi Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Anak muda penyandang disabilitas yang menggunakan TikTok untuk menyuarakan aksesibilitas transportasi umum, misalnya, berhak mendapatkan ruang aman tanpa stigma.
Aktivisme digital bukan sekadar tren. Ia adalah bentuk partisipasi sipil yang dijamin konstitusi dan menjadi napas demokrasi modern. Menurut Bung Hatta, “Indonesia merdeka bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.” Dalam semangat ini, generasi muda dengan segala kreativitas dan keberaniannya adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan suatu bangsa. Melalui dukungan hukum yang inklusif dan kesadaran kolektif, kita dapat memastikan bahwa setiap suara, termasuk yang lahir dari gawai dan media sosial, berkontribusi pada perubahan yang lebih bersifat untuk mewujudkan keadilan.
Dalam perspektif Islam, aktivisme digital yang dilakukan oleh generasi muda dapat dilihat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip amar ma’ruf nahi mungkar yang diatur dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman dalam Surat Ali ‘Imran (3:104), “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, dan menyuruh kepada yang makruf serta mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”. Ayat ini menekankan pentingnya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam. Dengan demikian, partisipasi anak muda dalam aktivisme digital adalah suatu bentuk kontribusi yang tidak hanya bermanfaat bagi mereka sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas.
Selain itu, tantangan yang mereka hadapi, termasuk praktik gaslighting, tidak sepatutnya dihadapi dengan reaksi negatif. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan teladan tentang pentingnya saling menghormati dan mendengarkan suara setiap individu. Sebagaimana hadits, dari Hamzah Anas bin Malik ra, pembantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna), sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Ini menunjukkan bahwa penghargaan dan dukungan terhadap suara anak muda dalam konteks aktivisme digital adalah bagian dari sikap saling mencintai dan menghormati antar sesama, yang merupakan prinsip dasar dalam Islam. Al-Qur’an juga menegaskan pentingnya keadilan dan penghindaran dari perbuatan yang merugikan orang lain dalam Surah Al-Maidah (5:8), “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Bahwa dengan demikian, memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak muda untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam aktivisme digital adalah tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai sosial, tetapi juga sesuai dengan petunjuk syar’i yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak berbicara setiap individu.