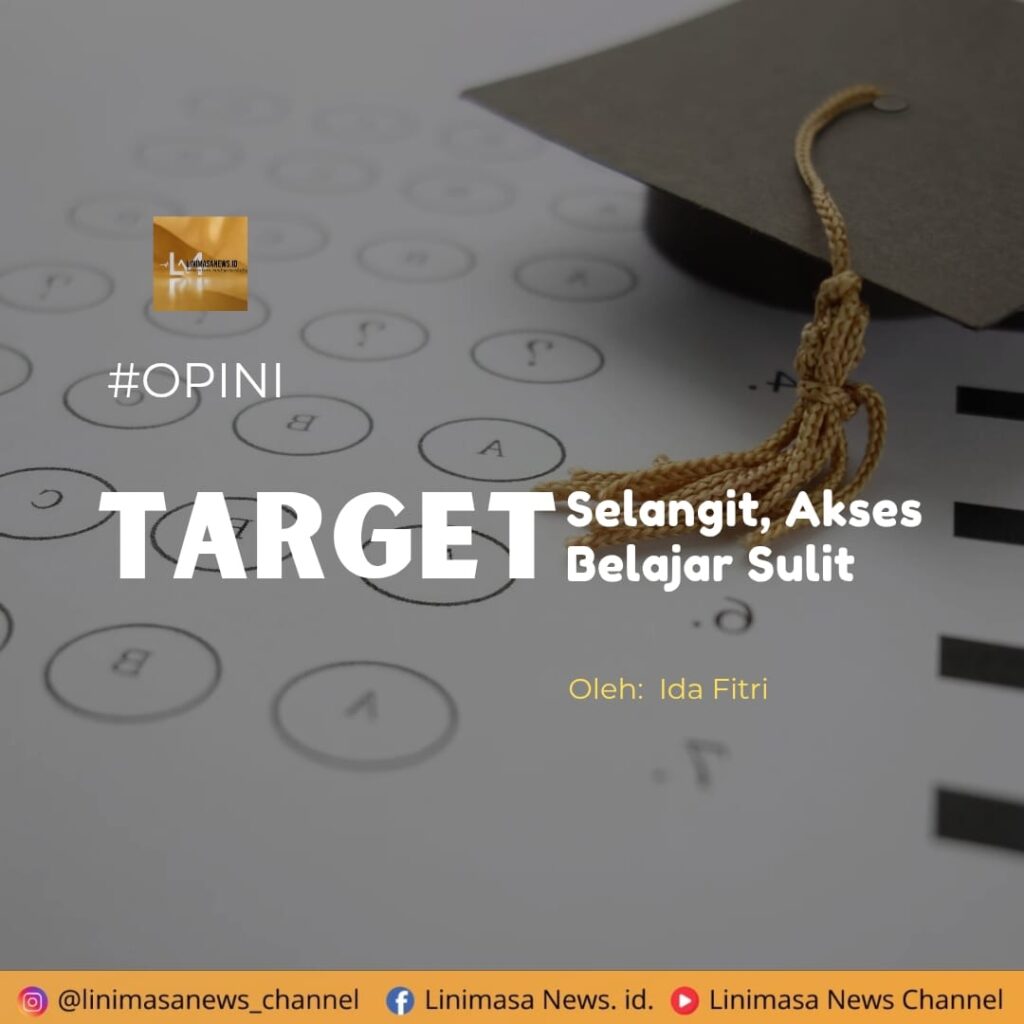
Oleh : Ida Fitri (Pemerhati Pendidikan)
Linimasanews.id—Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan atau sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun. Ini setara dengan lulusan kelas 9 atau sekolah menengah pertama (SMP). Temuan ini menjadi cerminan bahwa Pendidikan Indonesia masih didominasi oleh capaian jenjang menengah pertama dan banyak penduduk belum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi (Beritasatu.com, 02/05/2025).
Ironis memang. Setiap 2 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional, tetapi kenyataannya masih banyak generasi yang belum mampu mengenyam pendidikan tinggi. Rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya setara SMP. Ini akibat sistem kapitalisme yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas, sehingga akses bergantung pada kemampuan ekonomi. Sedangkan, masyarakat masih banyak yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan angka kemiskinan yang tinggi, tentu makin sulitlah rakyat mengakses pendidikan, sekalipun pendidikan dasar.
Negara memang sudah memberikan berbagai program sebagai solusi, seperti kartu Indonesia pintar (KIP), sekolah gratis, atau berbagai bantuan yang lain. Namun realitanya, belum semua rakyat berhasil mengakses layanan pendidikan, apalagi program tersebut hanya untuk kalangan tertentu, dan jumlahnya terbatas. Belum lagi, keberadaan layanan pendidikan yang tersedia tidak merata di semua wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Pendidikan saat ini ibarat barang mahal yang sulit dijangkau, terutama pendidikan tinggi, sekalipun sang anak pintar. Apa mau dikata, uang yang berbicara. Terlebih lagi bila anak memiliki kemampuan dan keuangan juga biasa saja, hanya berbekal semangat, maka hanya ibarat pungguk merindukan bulan.
Pada akhirnya, pendidikan hanya milik mereka yang memiliki harta. Untuk menembus perguruan tinggi butuh kemampuan yang memadai. Akhirnya yang mempunyai harta bisa meraihnya karena bisa mencari pelajaran tambahan di tempat-tempat les atau bimbingan belajar yang terkenal dengan biaya yang tidak murah. Memang ada siswa pintar dan bisa mengenyam pendidikan tinggi dari kalangan menengah bawah. Akan tetapi, persentasenya kecil sekali, 1 banding 10. Alhasil, generasi memilih mencukupkan diri dengan pendidikan rendah, yang penting bisa bekerja.
Sesungguhnya swastanisasi, mahalnya biaya pendidikan, ketimpangan akses dan kurikulum pasar telah menjadikan pendidikan hanya sebagai alat mencetak tenaga kerja murah, menguntungkan pengusaha. Sementara, generasi hanya menjadi buruh demi memenuhi kebutuhan industri. Akhirnya, pendidikan bukan hak dasar rakyat. Kondisi ini akan diperparah dengan adanya efisiensi anggaran.
Sementara itu, dalam sistem Islam (khilafah), pendidikan adalah hak setiap warga, miskin ataupun kaya. Negara wajib menyediakannya secara gratis dan merata untuk membentuk manusia berilmu dan bertakwa juga berketerampilan tinggi.
Khilafah memiliki sumber dana yang mumpuni untuk mewujudkannya. Dana pendidikan diambil dari Baitul Mal, khususnya pos fai’, kharaj dan kepemilikan umum (tambang, misalnya). Negara mengelola langsung pendidikan tanpa campur tangan swasta yang bisa mempengaruhi, apalagi mendikte kurikulum agar sesuai pesanan.
Sungguh indah hidup dalam naungan sistem Islam. Sistem demikian niscaya mampu mencetak ilmuwan yang ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat, serta bisa diamalkan pada generasi berikutnya.


