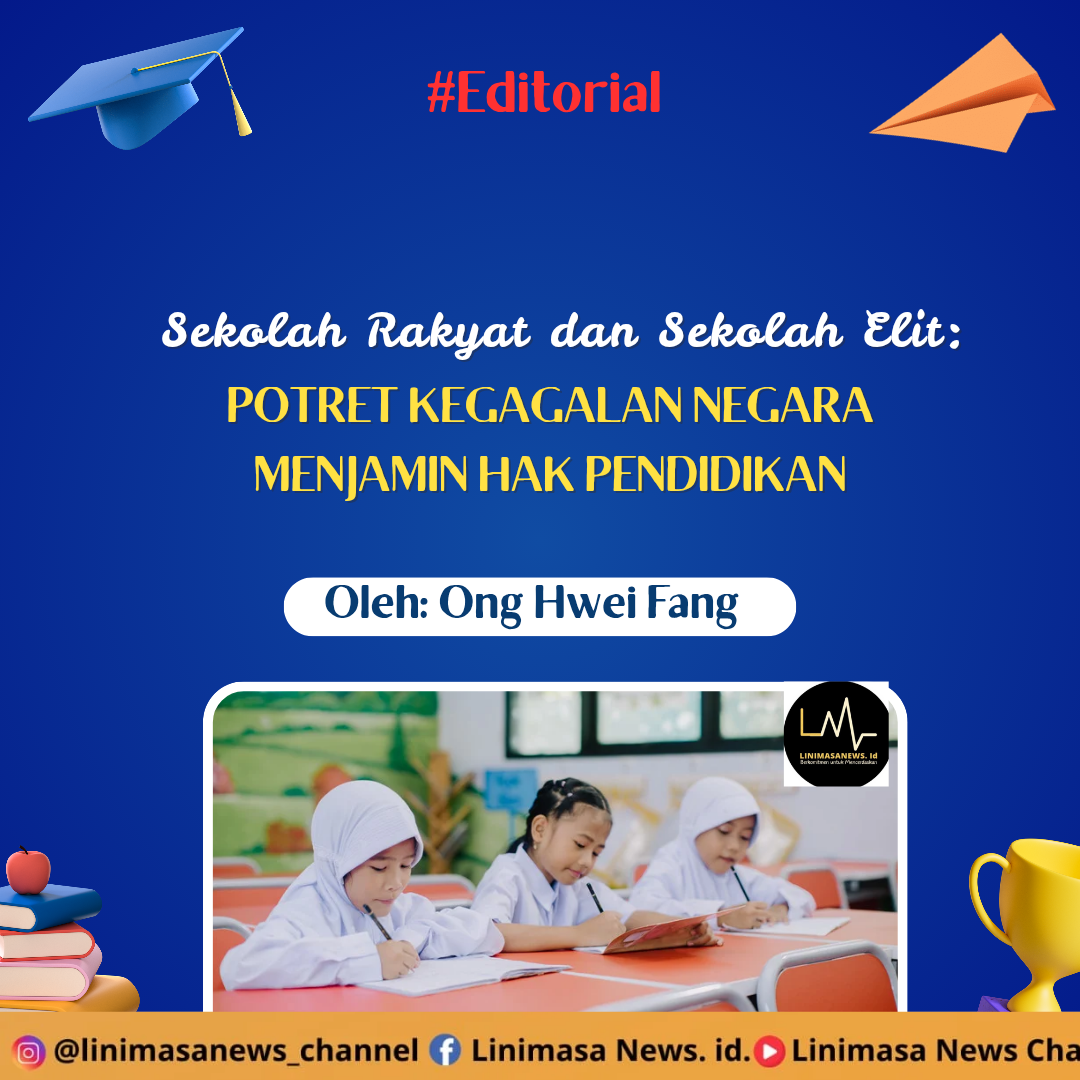
Editorial—Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru menjadi korban utamanya. Namun kenyataannya, hingga hari ini, jutaan anak di Indonesia masih menghadapi kenyataan pahit: putus sekolah bukan karena kurangnya minat, melainkan karena terjerat dalam kemiskinan struktural. Data dari Tirto.id menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama anak-anak di Indonesia tidak bersekolah. Ini adalah sinyal kuat bahwa pendidikan belum sungguh-sungguh menjadi hak universal, melainkan masih menjadi hak istimewa yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu.
Program-program bantuan seperti dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar telah lama diluncurkan sebagai upaya intervensi negara. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan. Alih-alih mencabut akar persoalan, kebijakan ini justru seringkali hanya menjadi bantalan sementara bagi keluarga miskin. Beban biaya pendidikan memang sedikit tereduksi, tetapi beban sistemik ketimpangan tak kunjung diurai. Sekolah masih jadi beban pikiran bagi para orang tua miskin, bukan menjadi harapan yang menenangkan.
Dalam skema terbaru pemerintahan Prabowo, muncul kebijakan Sekolah Rakyat, sebuah bentuk baru intervensi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, ada Sekolah Unggulan Garuda, yang ditujukan untuk kalangan ekonomi atas. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai jalan tengah untuk pemerataan akses pendidikan. Namun secara substantif, ini justru menunjukkan pemisahan kelas yang dilembagakan yakni sekolah untuk si miskin dan sekolah untuk si kaya, dalam sistem yang sama namun dengan kualitas, fasilitas, dan orientasi yang berbeda.
Ini bukan sekadar dikotomi teknis, melainkan gambaran gamblang dari cara sistem kapitalisme memperlakukan pendidikan sebagai produk yang bisa dikustomisasi sesuai daya beli. Negara tidak lagi hadir sebagai penyelenggara utama pendidikan rakyat, melainkan sebagai fasilitator pasar dan membiarkan masyarakat memilih “paket pendidikan” sesuai kemampuan mereka. Ketika pendidikan direduksi menjadi komoditas, maka hilanglah esensinya sebagai hak dasar.
Islam memandang pendidikan dengan paradigma yang sangat berbeda. Pendidikan adalah hak syar’i yang melekat pada setiap individu, sebagaimana hak atas makanan, kesehatan, dan keamanan. Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Sumber pembiayaan berasal dari Baitul Maal, bukan dari hutang, swasta, atau iuran masyarakat. Tidak ada konsep “sekolah murah” atau “sekolah mahal”, karena tidak ada yang perlu membayar untuk haknya sendiri.
Lebih dari itu, pendidikan dalam Islam bukan sekadar sarana agar rakyat dapat bekerja atau mencetak angka pertumbuhan ekonomi. Tujuannya lebih agung: mencetak generasi Muslim yang memiliki kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah), menguasai ilmu dan teknologi, serta siap mengemban misi dakwah dan membangun peradaban mulia. Pendidikan dalam Islam adalah investasi peradaban, bukan sekadar alat kebijakan populis.
Kebijakan tambal sulam seperti Sekolah Rakyat hanyalah upaya kosmetik yang tidak akan pernah menyentuh akar masalah. Ketimpangan pendidikan bukan persoalan teknis, melainkan persoalan sistemik. Ketika sistem yang digunakan adalah sistem kapitalisme yang menempatkan rakyat sebagai konsumen, bukan sebagai pemilik hak, maka pendidikan hanya akan menjadi impian bagi yang tak mampu membelinya.
Sudah saatnya kita berpindah dari pendekatan subsidi menuju pendekatan tanggung jawab penuh negara. Pendidikan bukan sekadar program bantuan, melainkan amanah besar yang tak bisa diserahkan pada logika pasar. Negara wajib hadir bukan hanya sebagai penyedia, tetapi sebagai penanggung jawab tunggal. Bukan karena kebaikan hati, tetapi karena itulah fungsi sejatinya. Dan Islam telah membuktikan, selama berabad-abad, bagaimana peradaban besar lahir dari pendidikan yang bebas biaya, berbasis akidah, dan berorientasi peradaban. Hal ini dikarenakan mendidik generasi bukan sekadar tugas, tetapi kewajiban yang menentukan arah masa depan umat manusia.[OHF]


