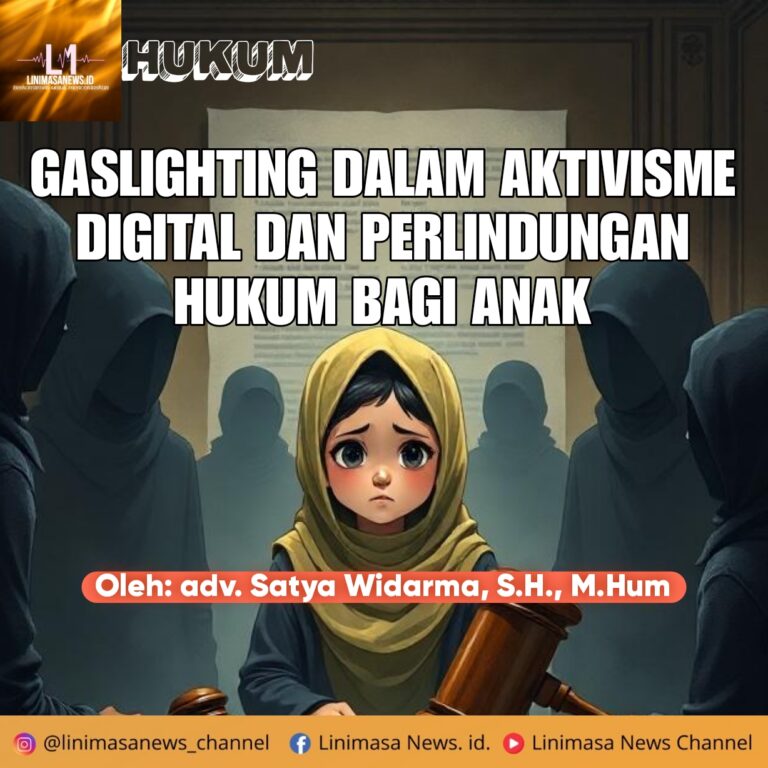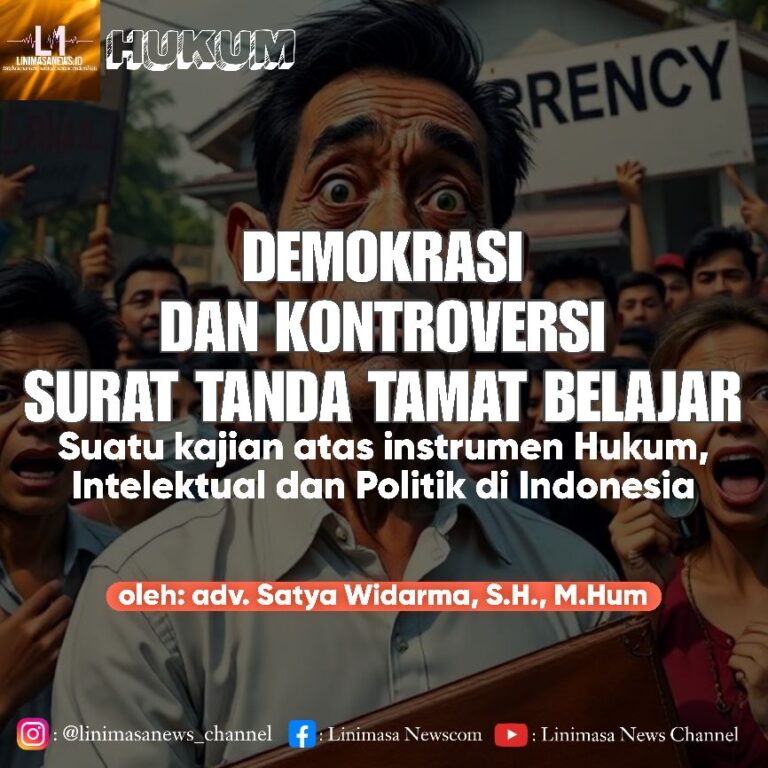Oleh : Satya Widarma, S.H., M.Hum
Linimasanews.id─Limerence merupakan suatu konstruk psikologis yang merujuk pada kondisi seseorang dengan ketertarikan emosional yang bersifat intens, obsesif, dan unilateral terhadap subjek tertentu (limerent object). Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara akademis oleh Dorothy Tennov melalui karya ilmiahnya berjudul Love and Limerence: The Experience of Being in Love (1979), yang mendefinisikan limerence sebagai suatu kondisi afektif yang timbul secara involunter, bersifat irasional, dan sulit untuk dikendalikan secara volisional (berkaitan dengan pengambilan keputusan atau tindakan yang dihasilkan dari kemauan seseorang). Berbeda dengan relasi afektif yang bersifat timbal balik (mutual affection), limerence bersifat asimetris (ketidakseimbangan dalam perasaan atau ketertarikan antara dua individu. Satu pihak mungkin mengalami perasaan cinta yang mendalam dan obsesi terhadap orang lain, sementara pihak yang lain mungkin tidak merasakan hal yang sama atau tidak memiliki perasaan yang sebanding) dan kerap menimbulkan distorsi kognitif (menyimpang dari kenyataan) yang dapat membuat individu mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan penderitaan emosional yang signifikan, terutama ketika perasaan tidak terbalas atau ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan.
Secara teoritis, Tennov mengemukakan bahwa limerence berkembang melalui tiga tahapan progresif: (1) fase infatuation (keterpikatan awal), (2) fase crystallization (pembentukan konstruksi mental yang bersifat fantastis), dan (3) fase deterioration (penurunan intensitas emosional akibat ketiadaan respons yang diharapkan). Proses neuropsikologis yang mendasarinya melibatkan stimulasi sistem dopaminergik pada ventral tegmental area (VTA) otak, yang secara patologis menyerupai mekanisme reward system pada kondisi adiktif, atau dengan kata lain, proses di otak yang terjadi saat mengalami limerence melibatkan aktivitas pada area ventral tegmental area (VTA), yang berhubungan dengan sistem penghargaan. Ini mirip dengan mekanisme yang terjadi saat seseorang kecanduan sesuatu, di mana otak merasa terstimulasi dan mendapatkan “hadiah” yang membuat individu merasa senang.
Berdasarkan kajian literatur terkait, limerence memiliki hubungan yang berkesinambungan dengan gangguan kelekatan (attachment insecurity) dan ketidakstabilan emosional yang bersumber dari pengalaman perkembangan individu pada masa kanak-kanak. Temuan empiris Fisher et al. (2010) dalam Journal of Neurophysiology mengonfirmasi adanya aktivasi berlebihan pada sistem limbik, yang secara klinis dapat diklasifikasikan sebagai disregulasi emosional. Sistem limbik adalah bagian otak yang mengatur emosi, perilaku, dan memori. Struktur utamanya meliputi amigdala, yang memproses emosi seperti rasa takut; hipokampus, yang penting untuk pembentukan memori; korena cingulate, yang terlibat dalam pengendalian emosi dan perhatian; serta hipotalamus, yang mengatur fungsi tubuh seperti tidur dan nafsu makan. Secara keseluruhan, sistem limbik membantu kita merespons lingkungan melalui emosi dan memori. Limerence mengaktifasi sistem ini secara berlebihan.
Dalam konteks intervensi terapeutik (pendekatan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh profesional kesehatan, seperti dokter, psikolog, atau terapis, untuk membantu individu mengatasi masalah kesehatan mental, emosional, atau fisik), pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) diakui secara klinis sebagai modalitas penanganan yang efektif, dengan menerapkan teknik mindfulness dan reality testing untuk memodifikasi atau merekayasa pola pikir yang maladaptif. Rekomendasi ilmiah dari Journal of Clinical Psychology (2018) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) dalam menangani dampak psikopatologis dari limerence.
Secara yuridis, meskipun limerence tidak diklasifikasikan sebagai gangguan mental dalam instrumen diagnostik seperti DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition : adalah panduan yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA) untuk diagnosis gangguan mental) atau ICD-11 (International Classification of Diseases, 11th Revision : adalah sistem klasifikasi penyakit dan kondisi kesehatan yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)), implikasi psikososialnya seperti penurunan kapasitas fungsional, gangguan penyesuaian diri, atau distres emosional, dapat menjadi pertimbangan hukum dalam konteks capacity assessment atau kasus-kasus perdata tertentu, sehingga pemahaman komprehensif mengenai aspek psikolegal dari limerence diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak yang terdampak.
Dalam pengaturan hukum Indonesia, kapasitas hukum seseorang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pihak yang mengalami gejala limerence mungkin mengalami penurunan dalam kemampuan untuk membuat keputusan secara rasional, yang dapat memengaruhi keabsahan kontrak atau transaksi hukum lainnya. Jika limerence menyebabkan gangguan yang signifikan, individu tersebut atau keluarganya mungkin dapat meminta agar mendapatkan perlindungan hukum atau pendampingan. Dalam kasus tertentu, dapat berupa pengajuan permohonan pengampuan jika individu dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa orang yang tidak mampu mengurus diri karena keadaan sakit otak tertentu dapat diajukan permohonan pengampuan, sekalipun terkadang di kesempatan lain, orang itu cakap dalam menggunakan pikirannya. Dalam perkara perdata, seperti perceraian atau sengketa hak asuh anak, pengadilan mungkin mempertimbangkan faktor psikologis, termasuk dampak dari limerence. Jika salah satu pihak dapat membuktikan bahwa limerence berdampak negatif pada kesejahteraan emosional mereka atau kapasitas mereka untuk menjalankan tanggung jawab, hal ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam putusan pengadilan.
Secara umum, jika limerence menyebabkan seseorang menjadi korban kekerasan emosional atau psikologis, hukum Indonesia di bawah Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat memberikan perlindungan. Meskipun limerence tidak diakui sebagai gangguan hukum, efek psikologisnya mungkin termasuk dalam definisi kekerasan, dan korban dapat mengajukan pengaduan masyarakat serta meminta perlindungan hukum. Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak limerence, sangat penting bagi praktisi hukum dan profesional di bidang kesehatan mental, bekerja sama untuk memahami dan menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan psikolegal individu. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan ada kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya kesehatan mental dalam konteks hukum dan perlindungan hak-hak individu di Indonesia.