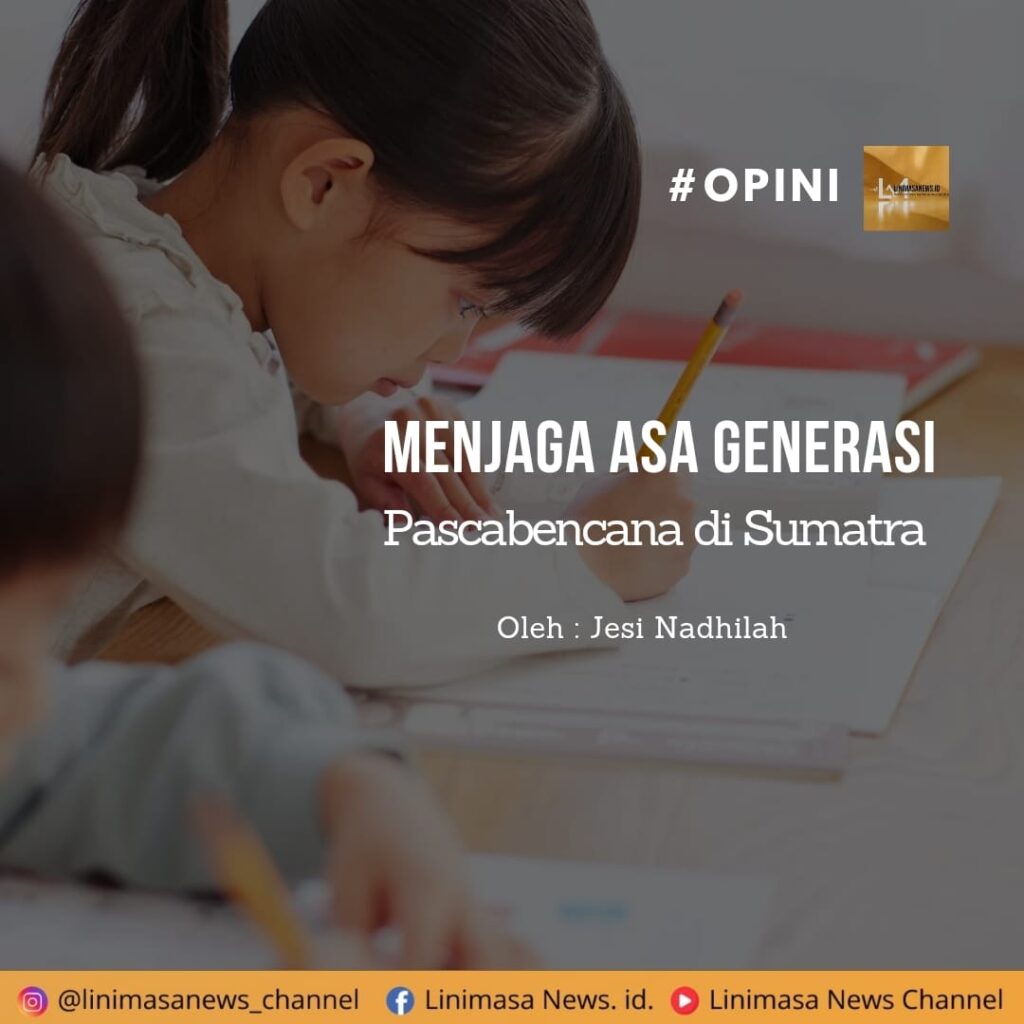
Oleh: Jesi Nadhilah
(Pengajar dan Aktivis Muslimah)
Linimasanews.id—Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra meninggalkan dampak serius bagi sektor pendidikan. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti memaparkan fakta yang tidak ringan: 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan. Banyak sekolah tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sebagian bangunan rusak berat, akses menuju sekolah terputus, bahkan tidak sedikit sekolah yang dialihfungsikan menjadi posko pengungsian.
Kondisi ini jelas memutus mata rantai pendidikan anak-anak yang seharusnya tetap terjaga, bahkan dalam situasi darurat. Di sisi lain, pernyataan Presiden yang menyebut kondisi Sumatra pasca bencana “dalam keadaan baik” menimbulkan jarak antara narasi resmi dan realitas di lapangan. Bagi anak-anak yang kehilangan ruang belajar, bagi guru yang kesulitan mengajar, dan bagi orang tua yang cemas akan masa depan pendidikan anaknya, “baik” tidak sekadar berarti situasi aman dari bencana lanjutan. “Baik” seharusnya dimaknai sebagai pulihnya layanan dasar, terutama pendidikan sebagai hak fundamental generasi.
Sayangnya, penanganan pascabencana terkesan lamban, khususnya dalam pemulihan sarana dan prasarana pendidikan. Proses rehabilitasi sekolah berjalan tidak sebanding dengan urgensi kebutuhan siswa. Ketika pendidikan tertunda terlalu lama, yang terancam bukan hanya capaian akademik, tetapi juga keberlangsungan masa depan generasi terdampak bencana.
Kondisi ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada klaim stabilitas, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret dan cepat. Menjamin hak anak atas pendidikan yang layak adalah ukuran sejati keberpihakan negara, sekaligus fondasi untuk menjaga harapan dan masa depan generasi Sumatra pasca bencana.
Bencana yang melanda sejumlah wilayah telah menyisakan luka mendalam, tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada rasa keadilan dan kepercayaan publik. Di tengah kondisi darurat, kesan lamban dan nirempati dari pemerintah pusat semakin menguat. Pernyataan normatif dan laporan administratif tidak sebanding dengan realitas lapangan yang dihadapi para korban, terutama generasi muda yang kehilangan ruang belajar, rasa aman, dan kepastian masa depan. Ketika empati negara seharusnya hadir lebih awal dan nyata, yang tampak justru jeda panjang antara bencana dan tindakan.
Sektor pendidikan menjadi contoh paling jelas dari kelambanan tersebut. Hingga waktu berlalu, belum terlihat respons cepat dan terukur untuk menangani kebutuhan pendidikan anak-anak terdampak. Sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan proses belajar terhenti tanpa solusi darurat yang memadai. Padahal, pendidikan bukan sekadar layanan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang menentukan arah hidup generasi pasca bencana. Ketika negara lambat bergerak, yang tertinggal bukan hanya bangunan, tetapi juga waktu belajar yang tak tergantikan.
Ironisnya, inisiatif nyata justru lebih banyak datang dari lembaga kemanusiaan, NGO, dan bahkan influencer. Mereka bergerak cepat menggalang bantuan, mendirikan sekolah darurat, menyediakan alat tulis, hingga menghidupkan kembali semangat belajar anak-anak di pengungsian. Kehadiran mereka patut diapresiasi, namun kondisi ini sekaligus membuka pertanyaan besar: di mana peran negara? Ketika aktor nonnegara mengambil alih fungsi yang semestinya dijalankan pemerintah, muncul kesan bahwa pemerintah pusat bersikap reaktif, bukan proaktif bahkan cenderung lepas tangan.
Kesan nirempati makin terasa ketika penderitaan korban direduksi menjadi angka dan laporan. Generasi yang terdampak diperlakukan seolah hanya sebagai objek statistik, bukan subjek yang memiliki hak dan kebutuhan mendesak. Padahal, empati negara tidak cukup diwujudkan lewat kunjungan simbolik atau pernyataan optimistis, melainkan melalui kebijakan cepat, anggaran yang sigap, dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Tanpa itu, narasi pemulihan hanya menjadi slogan kosong.
Situasi ini berbahaya dalam jangka panjang. Ketika negara gagal hadir secara nyata di saat krisis, kepercayaan publik terkikis. Generasi muda belajar satu pelajaran pahit: bahwa dalam kondisi paling genting sekalipun, mereka tidak sepenuhnya bisa bergantung pada negara. Jika dibiarkan, hal ini akan melahirkan apatisme sosial dan jarak emosional antara rakyat dan penguasa.
Penanganan bencana sejatinya berangkat dari aspek paradigmatik kepemimpinan. Dalam paradigma yang benar, pemimpin diposisikan sebagai pelayan dan pengurus rakyat, bukan sekadar pengelola administrasi negara. Orientasi ini menuntut kehadiran negara sejak awal bencana, bukan menunggu desakan publik atau viralitas. Rakyat yang tertimpa musibah tidak cukup diberi simpati, tetapi harus dijamin hak-hak dasarnya secara nyata dan segera.
Kesiapsiagaan tanggap risiko bencana menjadi konsekuensi langsung dari paradigma tersebut. Negara wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan asasi rakyat: keselamatan, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan bukan urusan sekunder pasca bencana, melainkan kebutuhan strategis agar generasi tidak kehilangan masa depan. Ketika sekolah rusak dan aktivitas belajar terhenti, negara seharusnya telah memiliki skema darurat kurikulum adaptif, sekolah sementara, serta dukungan psikososial bagi siswa dan guru.
Pemulihan infrastruktur juga menuntut respons cepat dan terkoordinasi. Pemerintah pusat tidak boleh bekerja sendiri atau saling lempar tanggung jawab dengan daerah. Koordinasi aktif dengan gubernur atau wali di wilayah terdampak harus dilakukan sejak fase awal. Negara perlu memobilisasi guru, mendistribusikan sarana belajar darurat, serta mempercepat rehabilitasi bangunan sekolah. Dalam fase pascabencana, kecepatan dan kejelasan komando menjadi penentu efektivitas pemulihan.
Jika dikomparasikan dengan fakta sejarah, penanganan bencana pada masa kekhilafahan menunjukkan paradigma yang berbeda. Negara hadir penuh sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Baitul Mal difungsikan untuk pembiayaan darurat tanpa menunggu prosedur berbelit. Pemimpin turun langsung memastikan distribusi bantuan, pemulihan fasilitas umum, dan keberlangsungan layanan pendidikan serta kesehatan. Rakyat tidak diposisikan sebagai beban, melainkan amanah.
Perbedaan ini juga tampak pada postur anggaran. Dalam sistem Islam, anggaran negara berorientasi pelayanan dan kebutuhan riil rakyat. Tidak ada konsep “penghabisan anggaran” di akhir tahun demi serapan administratif. Sebaliknya, dalam sistem kapitalisme, APBN sering terikat pada logika prosedural dan politik anggaran, sehingga respons terhadap bencana kerap lambat dan tidak optimal.
Dengan demikian, persoalan penanganan bencana bukan semata teknis, melainkan refleksi paradigma kepemimpinan dan sistem yang dianut. Selama pemimpin tidak memosisikan diri sebagai pengurus rakyat, dan selama anggaran tidak diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan, respons bencana akan terus tertatih dan hak generasi kembali menjadi korban.


